Jejak Madura dalam Literasi Budaya
Judul Buku : Kamis Pagi,
Pukul Sepuluh
Penulis : Nur Inayah, dkk.
Penerbit : Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
Kabupaten Sumenep
Cetakan : I, Desember 2017
Tebal :
148 halaman
ISBN :
978-602-391-510-1
Bakal Tolos, Bakal Burung karya Rofiki Asral, misalnya. Cerpen ini mengangkat cerita tentang
budaya pertunangan sejak bayi di Madura. Kisah ini mungkin dianggap hiperbolis,
tetapi kenyataannya Madura pernah atau sedang memiliki budaya seperti itu.
Kedua orangtua dari masing-masing calon ini memiliki andil besar. Proses
pertunangan tidak melibatkan si anak untuk menentukan calon tunangannya. Ironisnya,
terkadang si anak tidak tahu bahwa ia sedang menjalani proses pertunangan.
“Sehabis ibu
memandikanku, aku digendong menuju kamar. Di sini benar-benar aneh. Tak
biasanya kamar ini ikut ramai meski tak persis di dapur. Keluarga-keluarga
dekatku yang perempuan ada di sini. Mbak, bibi, nenek, semuanya. Aku duduk di
ranjang bersama mereka. Kemudian sambil bercakap-cakap denganku, mereka mulai
mendandaniku, memakaikan baju yang sepertinya baru” (hal. 14).
Tokoh aku dalam
cerpen ini digambarkan sosok lugu yang tidak mengetahui apa yang sedang
terjadi. Rofiki Asral sangat piawai menulis cerita dari sudut pandang anak
kecil. Keluguan, kepolosan, dan ketidaktahuan terhadap peristiwa di
sekelilingnya tergambar hingga akhir cerita.
Kisah lain, Penjung
karya Zainul Muttaqin juga mengangkat budaya Madura. Penjung adalah
sejenis selendang yang digunakan seorang penari tayub atau tandak. Seorang
penari tayub akan mengalungkan penjung kepada penonton. Berarti, penonton itu
berhak menari bersama penari tayub tersebut. Sebaliknya, penonton yang tidak
mendapat kalung penjung tidak diberi kesempatan menari bersama penari tayub. Ketika
menari, mereka diiringi musik gamelan khas Madura.
Tidak boleh seorang
pun menari dengan perempuan itu kecuali ia sendiri yang mengalungkan penjung di
leher lelaki yang beruntung, itulah aturan main yang harus diikuti. Tidak hanya
itu, siapa pun yang menerima penjung tidak boleh menyentuh tubuh sang tandak, apalagi
bertindak di luar batas. Hal ini diterapkan semata-mata supaya perempuan itu
tidak merasa dilecehkan harga dirinya sebagai seorang perempuan (hal. 24).
Orang Madura sangat
menjunjung tinggi harga diri. Seorang perempuan yang dilecehkan oleh orang
lain, keluarga atau suaminya akan bertindak secara tegas. Pepatah Madura “Lebbi
bhaghus pote tolang etembhang pote mata”, “Lebih baik putih tulang daripada putih mata”
masih melekat di benak masyarakat Madura. Masyarakat Madura lebih memilih mati
berkalang tanah daripada membiarkan harga diri terinjak-injak. Biasanya, jalan
yang ditempuh untuk mempertahankan harga diri adalah carok.
Judul Carok
juga ikut mengisi kumpulan cerpen dalam buku ini. Karya Fandrik Ahmad ini
mengangkat budaya carok yang terkenal hingga ke luar Madura. Fandrik Ahmad
menampilkan sosok aku yang menaruh dendam kepada Talhah, seorang lelaki yang
telah membunuh ayahnya. Sosok aku harus membalas dendam atas Talhah yang telah
menginjak-injak harga diri keluarganya. Hutang nyawa dibayar nyawa, begitu
mungkin yang terus bergemuruh dalam dirinya.
“Malam ini aku
mematangkan carok balasan kepada Talhah, seorang tengkulak yang telah membuat
nyawa bapak melayang demi kehormatan keluarga. Ya, Talhah kerap menggoda ibu di
bakap itu yang hampir setiap hari mencuci dan bersiraman di sana. Tak terima
dengan perlakuan itu, bapak menantang Talhah melakukan carok tanpa perhitungan
yang matang hingga kemudian nyawanya melayang.” (hal. 93).
Tokoh ayah dalam
cerita ini berada pada posisi yang “benar”. Ia ingin mempertahankan harga diri
keluarganya yang selama ini dijunjung tinggi. Walaupun dalam posisi yang benar,
tokoh ayah dalam keadaan tak berdaya menghadapi Talhah. Ia mati di ujung
celurit. Ironisnya, sosok aku yang berperan sebagai anaknya kini juga mengalami
nasib yang sama ketika menantang carok dengan Talhah.
“Celuritnya dibentangkan
di atas dadaku sebagai simbol kepuasan dan kebanggaan
atas kemenangan, sekaligus pengakuan bahwa dialah yang membunuhku. Bilapun
harus mati di ujung celurit, setidaknya, kehormatan keluarga telah kujunjung
tinggi” (hal. 98). Harga diri adalah segala-galanya. Tidak memiliki harga diri
sama halnya dengan menjalani hidup secara sia-sia.
Buku kumpulan cerpen ini telah merekam jejak-budaya Madura secara gamblang.
Sebagian, budaya tersebut telah punah, sebagian yang lain masih bertahan walaupun
laju perkembangan teknologi memasuki setiap perkampungan. Sayang, judul buku Kamis Pagi, Pukul Sepuluh ini tidak memberikan gambaran budaya Madura sebagai isi buku.
Kalau diamati, enam
dari sepuluh judul cerpen dalam buku ini lebih cocok dijadikan judul buku,
yaitu Bakal Tolos, Bakal Burung (Rifiki Asral, Sumenep), Penjung (Zainul
Muttaqin, Sumenep), Abhakalan Canting dan Alu (Wi Noya, Jakarta Timur),
Pasar Anom, Nabi Khidir, dan Hal-Hal yang Tidak Mungkin Saya Lupakan (Wahyudi
Kaha, Sumenep), Naon (Sengat Ibrahim, Sumenep), dan Carok
(Fandrik Ahmad, Jember). Judul-judul tersebut bisa mengaitkan memori pembaca
dengan budaya Madura, walaupun secara sekilas .
*Tulisan ini dimuat di Koran Tempo Akhir Pekan edisi 5793 Tgl 24-25 Maret 2018
**Suhairi adalah Dosen Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan Madura



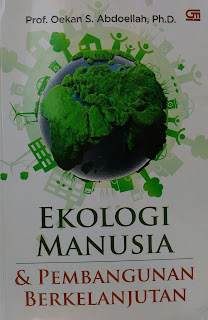
Komentar
Posting Komentar