Orang-Orang Malang
Dor! Dor! Dor!Dor!
Empat buah peluru menembus tubuh kakak kandungku, Mas Rizal. Darah muncrat
dari dada dan kepalanya. Kemudian tubuhnya tersungkur mencium tanah. Seluruh
tubuhnya dipenuhi darah. Nyawanya melayang setelah bunyi dor yang keempat
keluar dari moncong pistolku. Sementara sopir pribadinya terlihat panik.
Apalagi mereka hanya berdua. Entah mengapa, ibu, ayah, dan Mas Aldi tidak ikut
menikmati liburan saat itu. Aku tidak mau tahu tentang hal itu. Yang penting
aku bisa tersenyum setelah berhasil membunuh Mas Rizal.
Kulihat wajah ibu begitu berduka ketika salah satu televisi menayangkan
peristiwa itu. Ibu sangat menyayangkan salah satu putranya meninggal secara
tidak wajar. Sebagaimana ibu, Mas Aldi juga merasakan duka yang sangat
mendalam. Baginya, terlalu banyak kenangan indah yang sulit dilupakan. Ketika
masih kecil, Mas Rizal dan Mas Aldi selalu bermain perang-perangan dengan
peralatan pistol-pistolan, mobil-mobilan, rumah-rumahan, dan tank yang terbuat
dari plastik.
Berbeda dengan ibu dan Mas Aldi, ayahku terlihat lebih tegar menghadapi
cobaan yang menimpa dirinya. Ketika diwawancarai oleh wartawan televisi, ayahku
hanya pasrah kepada Tuhan. Seandainya ayah tahu bahwa peluru yang menembus
tubuh Mas Rizal adalah peluru yang keluar dari moncong pistolku, mungkin ayah akan
tersenyum, sebagaimana senyum yang menyembul dari wajahku setelah berhasil
membidikkan puluru tepat mengena tubuh Mas Rizal. Selama ini, ayahlah
satu-satunya orang yang selalu membelaku ketika ibu dan kedua kakakku
memperlakukan aku secara tidak wajar.
Dua tahun berikutnya, terjadi peristiwa yang tidak berbeda dengan peristiwa
yang menimpa Mas Rizal. Mas Aldi mengalami nasib yang sama.
Dor! Dor! Dor! Dor!
Empat buah peluru menyambar tubuh Mas Aldi. Ia langsung terkulai lemas dan
tersungkur ke tanah. Dari ke jauhan, aku masih sempat melihat ibu berteriak
histeris dan kemudian tak sadarkan diri. Sedangkan ayah terlihat shock.
Tapi aku tidak begitu lama menyaksikan suasana duka mereka. Aku harus cepat
pergi sebelum polisi mengejar jejak kakiku. Kamudian aku pulang menghadap ayah
tiriku dan melaporkan bahwa aku sudah selesai melaksanakan agenda terbesarku;
membunuh kedua kakak kandungku.
********
Lembayung senja mencipratkan nuansa indah di pojok pekarangan rumahku.
Setiap senja, hanya lembayung itu yang bisa kuharap menebarkan sebuah
keindahan. Sesaat kemudian, aku tak bisa lagi menatapnya. Gelap telah merampas
keindahan lembayung senja dari tanganku.
Aku mulai menata tidurku setelah mengulang mata pelajaran untuk hari esok.
Aku tak diperbolehkan nonton televisi atau mendengarkan radio, tidak seperti
halnya kedua kakakku. Mereka lebih leluasa menikmati fasilitas yang ada di
rumah. Mereka bebas nonton televisi dan mendengarkan radio kapan saja mereka
suka. Mereka juga sering bepergian keluar kota; rekreasi ke tempat-tempat yang
indah atau sekedar makan di sebuah restoran mahal. Itu informasi yang kudapat
dari tetangga sebelah yang merasa iba terhadap keberadaanku.
Aku tidak heran bila teman-teman sekolahku sering mengejekku bahwa aku anak
tiri. Mereka mengatakan bahwa aku anak
buangan yang ditemukan di tong sampah. Mereka juga bilang bahwa aku anak zina.
Hal itulah yang menata keyakinanku bahwa statusku di tengah-tengah keluarga ini
adalah sebagai anak tiri.
“Kamu jangan sok pintar di sekolah ini. Kamu anak tiri!”
“Aku bukan anak tiri. Aku anak kandung dari ibuku. Aku juga punya dua kakak
kandung.”
“Bu Indah bukan ibu kandungmu, ia ibu tirimu. Kedua kakakmu
itu juga kakak tirimu.”
Aku hampir menangis karena tak tahan mendengar ejekan teman-teman. Walaupun
demikian, mereka tak henti menghinaku.
“Lihat, kamu tidak dibelikan baju seragam sekolah seperti kedua kakakmu
itu. Kamu beli baju seragam dari hasil jualan jeruk dan es, kan?”
Ejekan seperti itu hampir setiap hari menempel di daun telingaku. Tapi aku
bukan anak tiri sebagaimana yang mereka katakan selama ini. Aku sempat melihat
sendiri akte kelahiranku. Jelas, namaku tertulis di antara deretan nama yang
lainnya. Dan itulah salah satu saksi
bahwa aku anak kandung dari ibuku yang sangat kejam.
Aku memang tak dibelikan pakaian seragam; baju putih, celana merah, topi,
dan sepatu. Mainanku juga tak selengkap mainan yang dimiliki kedua kakakku.
Mereka mempunyai pistol-pistolan, mobil-mobilan, rumah-rumahan, dan tank yang
terbuat dari plastik. Semua permainan itu bisa berfungsi sebagaimana pistol
sungguhan, mobil sungguhan, rumah sungguhan, dan tank sungguhan. Sehingga,
kedua kakakku itu sering beramain perang-perangan.
Aku pernah bilang kepada ibu agar aku diperbolehkan bermain perang-perangan
dengan mereka. Tapi aku dimarahi. Menurut ibu, aku tidak mempunyai peralatan
yang lengkap untuk ikut main perang-perangan. Seharusnya aku diperlakukan sama
dengan kedua kakakku. Bukankah aku mempunyai hak dan kewajiban yang sama?
Bukankah aku juga mempunyai tantangan dan peluang yang sama? Tapi mengapa nasib
yang menimpaku tak seindah nasib yang dimiliki kedua kakakku. Aku tak berani
membantah dan menatap wajah ibu. Aku mundur sambil menunduk dengan langkah yang
sangat pelan.
Keadaan seperti itulah yang membuatku kabur dari rumah. Keputusanku kabur
dari rumah ternyata tidak mampu mengubah nasibku menjadi lebih baik. Aku diasuh
oleh seorang lelaki yang lebih kejam dari ibu dan ayahku. Ini tercium sejak aku
melihat aksesoris yang menempel pada dinding rumah, seperti sebuah pistol yang
sengaja di taruh di dinding kamar. Di sebelahnya terdapat sebuah celurit besar
yang seakan siap menebas tubuh lawan.
Sebulan lebih aku berusaha mengorek informasi tentang ayah tiriku.
Ternyata, ayah adalah salah seorang yang bergabung dalam sindikat penjualan
narkoba internasional. Keberadaan sindikat itu sangat rapi. Sehingga hal
tersebut tak bisa tercium oleh aparat. Ayah juga bisa hidup dengan leluasa.
“Bagaimana, kamu kerasan di rumah ini?” Tanya ayah.
“Aku sangat senang, ayah,” jawabku walaupun dibuat-buat.
“Mulai saat ini, kamu harus banyak belajar!”
“Belajar apa, Yah?”
“Belajar membunuh!”
“Belajar membunuh?”
“Belajar menyelundupkan barang-barang!”
“Belajar menyelundupkan barang-barang?”
”Ya.”
”Maksud ayah?”
”Barang Haram.”
”Narkoba?”
”Pintar Kau!”
Aku kaget dan tertegun. Aliran darah dan sumsumku seakan terkena sihir.
Timbul penyesalan yang tiada tara, mengapa aku harus meninggalkan ibu tercinta,
ayah tersayang, dan kedua kakakku yang masih kuingat raut wajahnya. Mengapa aku
harus meninggalkan kampungku yang telah membesarkan aku dan telah mendidikku
sejak kecil. Mengapa dan mengapa!
Ayahku mendatangkan orang untuk mendidikku menjadi penyelundup andal. Aku
mengikuti perintah ayah walaupun terasa berat kulakukan. Apalagi aku bukanlah
orang yang berpengalaman dan berpendidikan tinggi. “Ini adalah kesempatan besar
buat kamu. Kamu tak mungkin dapat pekerjaan tanpa mempunyai ijazah. Apa kamu
mau jadi buruh kasar dengan bayaran kecil?” begitu ayah membujukku agar aku mau
melakukan apa yang ayah kehendaki.
Beberapa bulan berikutnya, aku sudah mulai belajar menggunakan pistol. Aku
agak kesulitan menggunakannya. Seandainya dulu aku diperbolehkan main
perang-perangan dengan kedua kakakku, mungkin aku tak terlalu sulit
mengoperasikan pistol. Ah, itu dulu. Yang lalu biarlah berlalu! Tak ada gunanya
mengenang masa lalu yang terlalu menyakitkan.
Aku berlatih memfokuskan dan mengkonsentrasikan pikiran. Semangat memainkan
pistol ternyata bersemi dengan indah di pelataran hatiku. Aku berlatih dengan
rajin dan giat. Entah mengapa, secara tiba-tiba terlintas kedua wajah kakakku
di pelupuk mata. Mereka seakan tersenyum dan mengejekku. Seakan-akan aku sedang
melihat mereka sedang menikmati liburan di sebuah taman yang sangat indah dan
di sebuah hotel berbintang. Aku semakin konsentrasi membidikkan peluru pada
bayangan wajah mereka. Aku ingin memecahkan kepalanya, menembus jantungnya,
memecahkan kedua bola matanya. Apalagi, selama ini mereka tak pernah
merasakan kegundahan hati yang selama ini melilit kehidupanku. Mereka selalu
menganggapku bukan saudara kandung. Ah, biadab!
Dor! Dor! Dor! Dor!
“Bagus! Lebih fokus dan lebih
konsentrasi!” kata guru privatku.
“Fokus dan konsentrasi?”
“Fokus pada satu titik dan konsentrasinya tidak boleh buyar.”
“Ya, ya, ya…!”
Dor! Dor! Dor! Dor!
Empat peluru mengena empat sasaran tanpa meleset sedikitpun. Aku menarik
nafas lega. Begitu juga ayah dan guru privatku. Mereka tampak sumbringah
melihat prestasi yang telah kumiliki.
Suatu malam, aku berbicara empat mata dengan ayah tiriku bahwa aku akan
membalas sakit hatiku pada kedua kakakku. Ayah tersenyum bangga. Niat busukku
itu merupakan keberhasilan ayah mendidikku menjadi seorang penjahat. Tapi aku
tak perduli apakah aku disebut sebagai penjahat atau bukan.
************
Selama ini memang tak ada seorangpun yang mengharagai hidupku, kecuali ayah
tiriku. Hingga akhirnya aku berhasil menjadi penyelundup barang haram dan
menjadi pembunuh kelas kakap. Aku berhasil membunuh Mas Rizal. Masih teringat
di benakku, empat peluru menembus tubuhnya. Dua tahun berikutnya, aku berhasil
membunuh kakak kandungku yang lain, Mas Aldi. Empat peluru juga menembus
tubuhnya.
Kematian kedua kakakku menyisakan duka yang sangat mendalam, terlebih lagi
bagi ibuku. Tapi seperti itulah alur yang telah terjadi. Aku merasa kasihan
kepada ibu dan ayah kandungku. Mudah-mudahan mereka mampu mengatasi duka yang
cukup menyiksa. Mudah-mudahan mereka juga tak mengutukku menjadi batu,
sebagaimana ibu Malin Kundang mengutuknya menjadi batu. Ibu, maafkan
aku! Suatu saat, aku akan kembali ke pangkuanmu. Aku akan membayar hutangku
sebagai seorang anak durhaka dengan air mata, darah, dan nyawa. Kali ini aku
hanya ingin membuat prasasti bahwa ketidakadilan pasti menuai petaka.
Aku dan ayah tiri mengadakan pesta kemenangan. Beberapa anak buah ayah juga
ikut merayakannya. Ini adalah pesta terindah dan pesta terlama yang
pernah aku rasakan. Kami mengadakan pesta minuman keras ditemani
perempuan-perempuan modis dengan dandanan minor. Sejak pagi, hingga larut
malam.
Aku semakin mengagumi sosok ayah tiri. Walaupun sepak terjangnya sempat
beberapa kali tercium aparat, tetapi ayah pandai memasang umpan. Pasti ada
salah satu anak buahnya yang dibekuk aparat, sedangkan ayah bisa hidup aman
secara leluasa. Sebulan yang lalu misalnya, ayah hampir tertangkap basah
menyelundupkan barang haram ke Malaysia. Ah, bukan ayah jika tak pandai
memasang umpan. Ayah kabur dari tempat itu. Sedangan kedua anak buahnya dibekuk
aparat kepolisian.
Seminggu berikutnya. Jarum jam menunjukkan pukul 23:15. Aku teringat wajah
ibu dan ayah kandung. ”Apakah malam ini mereka masih berduka? Ataukah
sedang mengadakan pesta, sebagaimana aku berpesta beberapa hari yang lalu?”
Dor! Dor! Dor!Dor!
Ingatanku kembali melayang pada peristiwa maut. Mas Rizal dan Mas Aldi bersimbah
darah, setelah bunyi dor ke empat keluar dari moncong pistolku. Nah, apalagi
pekerjaan yang harus aku lakukan, jika semuanya telah terselesaikan dengan
baik?
Tok tok tok tok tok...!
Tok tok tok tok tok...!
“Siapa?” tanyaku dengan suara keras.
Braaakkkkkkk!!!!!!!!!!!!
”Angkat tangan, ikut kami ke kantor polisi,” mereka langsung memborgol
kedua tanganku.
”Maaf, ada apa, Pak? Aku bukan pembunuh!” Aku berusaha
memberontak.
”Tapi kau pengedar barang haram!” Kata salah satu di antara mereka, sambil
menggiring aku keluar.
”Aku bukan pengedar barang haram!” teriakku lagi.
”Tapi kau seorang penjahat!”
”Ayaaahhhhh!”
Rupa-rupanya rumah ini sudah kosong. Mungkin ayah sudah kabur, entah ke
mana. 21 Januari 2010.
*Tulisan ini dimuat
di Harian Seputar Indonesia, Minggu, 25 April 2010.


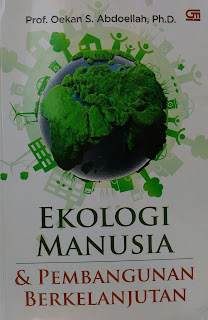
Komentar
Posting Komentar