Lampu Templek Mbah Sholeh
Lelaki yang biasa dipanggil Mbah Sholeh itu merebahkan tubuhnya di sebuah
ranjang tua. Sebentar kemudian ia terlelap. Ia terlalu capek setelah seharian
bekerja; mencangkuli sawah, memberi makan ternak, dan memandikan sapi. Ia harus
bangun pagi; mengaji Al-Quran sebelum subuh, mengumandangkan azan, membaca
dzikir dengan sisa-sisa suaranya yang tidak terlalu merdu, sambil menunggu
anak-anak tetangga mengaji Al-Quran. Setelah Sholat Dhuha, Mbah Sholeh
melakukan kegiatan rutinnya. Menjelang mahgrib ia sudah berada di Musolla.
Mengurusi anak-anak tetangga mengaji Al-Quran, menghafal sifat-sifat wajib dan
muhal bagi Allah dan Rosulnya. Setiap malam Sabtu anak-anak tidak usah mengaji
Al-Quran. Mereka belajar dan menghafal bacaan sholat-sholat fardlu.
“Mbah, Rani sudah bisa membaca Al-Quran sendiri, Mbah,” Kata Rani, salah
satu santrinya.
“Kalau Ahmad sudah hampir hatam Quran Kecil,” Ahmad tak mau kalah.
“Mbah, jika saya pandai mengaji Al-Quran, saya akan mengaji ke atas Mbah,
ya,” Romli juga menimpali santri yang lain seraya menunjuk ke arah lood
speaker.
Mbah Sholeh tersenyum bangga. Para santri kecil itu selalu menjadi pelipur
hati Mbah Sholeh manakala ia merasakan kegalauan dalam jiwanya. Hal itulah yang
membuat Mbah Sholeh bertahan menjadi guru mengaji mereka. Mbah Sholeh tak
pernah mengeluh walaupun ia tak mendapatkan suatu materi dari para orang tua
maupun dari pemerintah. Baginya, menularkan ilmunya kepada siapa saja yang
membutuhkan merupakan anugerah luar biasa.
Beberapa tahun berikutnya, santri kecil Mbah Sholeh banyak yang berhenti.
Ahmad melanjutkan ke pondok pesantren; Rani ikut ayahnya pindah tugas;
sedangkan Romli sudah semakin dewasa dan tidak mau lagi mengaji di Musolla Mbah
Sholeh. Beberapa santri yang lain juga ikut berhenti tanpa alasan yang jelas.
Kini, santri Mbah Sholeh tinggal empat anak. Keempat anak tersebut hanya
sebagian saja yang aktif. Bisa dipastikan tiap malam yang datang mengaji hanya
dua orang.
“Kalau memang yang mengaji Al-Quran hanya tinggal empat anak, kenapa tidak
disatukan saja dengan santrinya Kiai Mahfud,”usul Nyai Sholeh.
“Jangan bilang seperti itu, Nyai. Mereka kan mau mengaji Al-Quran kepada
saya. Mereka adalah amanah bagi saya.”
“Dengan menyerahkan mereka kepada Kiai Mahfud berarti Mbah masih
melaksanakan amanah.”
“Terus, Mbah mau kerja apa?”
“Ya, Mbah lebih enak, tidak usah ngurusi anak-anak nakal itu.”
Tiba-tiba tawa Mbah
Sholeh tumpah. Nyai Sholeh hanya tertegun. Nyai seius Mbah, pikir Nyai Sholeh.
Beberapa tahun berikutnya, desa itu semakin ramai dan semakin maju. Pembangunan
jalan raya sampai ke pelosok-pelosok. Listrik-listrik menerangi seisi desa
hingga ke tempat-tempat yang jarang dijangkau orang lewat. Hampir di setiap
atap rumah penduduk berdiri antena televisi.
Suatu malam, Pak Kadir bertamu ke kediaman Mbah Sholeh.
“Kok tumben datang kemari, Pak Kadir?” tanya Mbah Sholeh.
“Oh, maaf, Mbah! Sebenarnya, sudah lama saya ingin kemari, tapi belum ada
waktu.”
“Jadi baru sekarang sempatnya?”
“Iya, Mbah. Dan itupun mungkin saya tidak kemari lagi.”
“Memangnya ada apa?”
“Saya mohon doa restu Mbah, anak saya, Rahma, bulan depan akan saya
nikahkan.”
“Menikah?”
“Iya, Mbah. Saya mohon doa restu dari Mbah sekalian mohon maaf atas segala
kesalahan anak saya selama mengaji Al-Quran di sini.”
“Ooo, begitu.”
“Iya, Mbah.”
“Ya, tak masalah. Berarti santri Mbah tinggal dua anak. Setengah bulan
yang lalu, Nita juga keluar dari sini.”
Musolla Mbah Sholeh semakin sepi. Lampu templek yang menjadi penerang
anak-anak mengaji Al-Quran semakin meredup. Hingga suatu saat, musolla itu
betul-betul kosong. Tak ada anak kecil yang mau mengaji. Mbah Sholeh hanya
mampu mengurut dada sambil mengucap kalimat istighfar.
“Mbah seharusnya senang. Tidak ada lagi anak kecil yang mau menggangu
Mbah,” Nyai Sholeh berkomentar.
“Mereka tidak mengganggu. Mereka…..”Mbah Sholeh tidak mampu meneruskan
kata-katanya. Linangan air matanya menerobos melalui lekukan-lekukan
keriput pada wajahnya.
“Seharusnya Mbah senang. Bangun paginya tidak usah terburu-buru. Pulang
dari sawah sore hari juga tidak usah terburu-buru. Jadi sekarang bebas. Dan
bisa menanam padi lebih banyak lagi. Kalau nanti panen, hasilnya panennya kan
lebih banyak dan bisa dipakai buat beli lampu listrik dan televisi,” Nyai
Sholeh menghibur.
Mbah Sholeh menundukkan wajahnya. Pandangannya menerobos jauh ke alam
akhirat.
“Mengajari anak-anak membaca Al-Quran adalah amal Mbah Sholeh untuk bekal
menuju akhirat. Sebentar lagi kita akan menghadap-Nya. Lalu amal apa yang bisa
kita haturkan pada penguasa jagat ini?”
Air mata Mbah Sholeh
masih mengalir. Semakin deras. Semakin deras. Nyai Sholeh juga merasa
terharu. Ia tak kuasa menahan linangan air matanya. “Maafkan Nyai, Mbah!”
Mbah Sholeh menyalakan lampu templek. Yang satu untuk musolla, yang satunya
lagi untuk ruangan Mbah Sholeh. Di desa itu, hanya rumah Mbah Sholeh yang tidak
mendapat aliran listrik. “Mbah tidak mampu,” katanya ketika ditanya.
Walaupun di musolla Mbah Sholeh tak satupun anak kecil yang mau mengaji
Al-Quran, Mbah Sholeh senantiasa menyalakan lampu templek untuk menerangi
ruangan Musolla tersebut. Barangkali ada tetangga yang mau mengaji kepada saya,
atau solat berjamaah dengan saya, atau ada musafir yang ingin mampir ketika
seharian berjalan kaki, pikirnya.
Yang terpenting, setiap senja tiba, ia selalu menyalakan lampu templek
seraya menunggu mereka ‘mampir’ di musollanya, walaupun Mbah Sholeh tidak tahu
kapan dan siapa yang akan mendatangi musolla tersebut.
Di musolla Kiai Mahfud, tak seorang santripun yang mau mengaji Al-Quran.
Anak-anak kecil zaman sekarang lebih suka nonton televisi, ujar Kiai Mahfud,
suatu ketika.
“Lebih
baik saya matikan lampu templek ini. Sudah saatnya saya istirahat,” musolla itu menjadi
gelap. Mbah Sholeh berjalan tertatih-tatih. Esok paginya, tersebar kematian
Mbah Sholeh, namun tak seorangpun yang merasa kehilangan, selain Nyai Sholeh.
*Tulisan ini dimuat
di Majalah Mimbar Pembangunan Agama, Maret 2010.

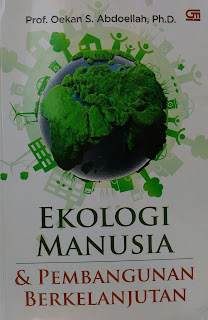

Komentar
Posting Komentar