Kugendong Rembulan
Tiba-tiba tangan dan kakiku
digerakkan makhluk ghaib yang berkekuatan tinggi. Secara sigap kedua kakiku
melangkah ke sana ke mari. Sedangkan kedua
tanganku mengumpulkan tangga dan tali pengikat. Beberapa saat kemudian,
berjuta-juta tangga berserakan di depanku. Kemudian kususun satu persatu dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian.
“Bulan, takluklah engkau dalam pelukanku!” batinku, seraya menyusun
tangga-tangga itu sampai tinggi.
Bulan begitu purna. Pancaran sinarnya menerangi seisi dunia. Dari ketinggian
ini pula, aku sempat menikmati keindahan alam semesta. Danau-danau, selat dan
samudera, gunung-gunung, pepohonan, juga keindahan-keindahan negeri yang
membentang luas dihiasi dengan warna indah rembulan, bagiku menjadi ibrah
kemahaindahan sang pencipta. Tuhan, bagaimana engkau melukis semua ciptaan-Mu
ini? Apakah sinar rembulan itu yang membuat indah segala ciptaan-Mu? Seingatku,
tak pernah kulihat dan kusaksikan pemandangan indah seperti ini. Seingatku
pula, sering kulihat asap pekat menggumpal di atas hutan lebat, laut sering
dicemari bahan peledak, kantor-kantor
dicemari penyelewengan dana, dan terjadi
saling sikut antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain. Tapi pemandangan
malam ini begitu indah. Suatu pemandangan yang betul-betul menyentuh perasaan
dan hatiku. Suatu pemandangan yang lebih tepatnya dikatakan sebagai pemandangan
yang kecipratan keindahan syurga. Begitu indah. Begitu memukau.
Subhanallaah!
Aku masih menyusun tangga pertangga. Entah semangat siapa yang telah
menyusup ke dalam sumsum dan darahku. Uniknya, setiap pengikat satu
tangga dengan tangga yang lainnya hanya dikerjakan dalam hitungan detik. Lembar
hatiku membisikkan kabar baik pada naluriku, bahwa tanpa melewati subuh
tangga-tangga ini akan mengantarkan aku menyentuh rembulan. Walaupun di sisi
lain aku yakin, bahwa tangga ini bukan buroq; kendaraan nabi ketika melakukan
Isro’ dari Mesjidil Haram ke Mesjidil Aqsho, atau ketika melintasi tujuh lapis
langit yang hanya dikerjakan kurang dari satu malam. Aku juga yakin, bahwa tangga-tangga
ini bukan pesawat Nil Amstrong yang mampu meninggalkan jejak sejarah di bulan.
Tanpa terasa, ternyata aku sudah hampir menyentuh rembulan itu. Mungkin
seratus atau dua ratus meter lagi. Aku terus menaiki tangga tanpa merasa lelah
dan letih sedikitpun. Di bawah sana, aku melihat orang-orang berkerumun
menyaksikan adegan yang kulakukan malam ini. Mungkin mereka juga bisa melihatku
dari jarak yang begitu jauh; dari bumi ke bulan. Aku melihat mereka ada yang
berbisik-bisik, ada pula yang melihatku merasa ngeri, ada pula yang tampak
ketakutan melihatku sebagai raksasa penakluk dunia, ada pula yang memukul-mukul
kentongan, ada pula yang mengucek-ngucek matanya, mungkin mengira ia sedang
bermimpi. Kemudian….
“Aku bisa menyentuh rembulan……!!!” teriakku ketika kali pertama tanganku
berhasil menyentuhnya.
“Aku bisa menyentuh rembulan…..!!! Akan kubawa rembulan ini menemui
orang-orang di bawah sana. Akan kugendong, lalu kuturuni tangga demi tangga
sambil mengucap syukur ke hadirat Ilahi Robbi.
Rembulan yang kini dalam gendonganku ternyata tak sebesar rembulan yang
diajarkan pak guru di sekolah. Rembulan ini sungguh indah. Kecil. Mungil. Dan
cukup untuk digendong. Bahkan, ia sempat bercakap-cakap selama kami menuruni
tangga pertangga.
”Mas, aku takut!” kata rembulan seraya memegang erat pundakku.
”Ah, tak usah takut, sayang. Kita akan baik-baik saja, kok. Selama aku berada di sampingmu, aku yakin
tidak akan terjadi apa-apa.”
”Tapi aku takut dengan ketinggian ini?”
”Aku akan hati-hati menuruni tangga ini, agar kita bisa selamat hingga
tangga terakhir dan hingga menyentuh bumi.”
Aku tersenyum kecil. Ternyata, bait sajak penyair ’ketika rembulan
berbicara’ bukan lagi bahasa kiasan. Ini adalah kenyataan. Akan kukabari
penduduk bumi bahwa para penyair telah kehilangan kata kiasan. Maka
bersiap-siaplah para penyair kecewa atas kejadian ini. Apalagi, mereka selalu
mengandaikan rembulan itu betul-betul berbicara, tersenyum, bahkan bercinta.
Dan orang yang pertama kali mampu melakukan itu adalah aku; sang penakluk rembulan.
”Mas, aku takut!”
”Sssst..., tahan sebentar lagi. Kita akan sampai di planet bumi.”
”Aku takut penduduk bumi akan mengejar-ngejarku. Memperkosaku. Bahkan
membunuhku. Bukankah pekerjaan mereka selalu bertengkar. Mengadu domba.
Menumpahkan darah.”
”Ah, itu fitnah. Dari mana kamu tahu semua itu?”
Ia terdiam. Namun, ia mempererat dekapan tangannya agar tak terjatuh ke
bumi. Aku terus menuruni
tangga dengan sangat hati-hati. Hanya tersisa beberapa tangga lagi. Orang-orang
mulai betepuk tangan atas keberhasilanku menaklukkan rembulan.
Namun, sebelum kedua kakiku menyentuh tangga terakhir, tiba-tiba ada
tangan-tangan raksasa yang memegang kedua kakiku. Aku hampir terjatuh. Untung
saja aku mampu menguasai keseimbangan. Sedangkan rembulan semakin mempererat cengkraman
tangannya. Namun,
tangan-tangan raksasa itu terus menarik-narik kedua kakiku. Entah dari mana
datangnya tangan-tangan tersebut.
“Aku takut! Mas, ayo bangun, Aku takut!”tiba-tiba kudengar sebuah suara. Mirip suara isteriku.
“Ayo bangun, Mas! Bangun, Mas! Sudah hampir subuh. Sholat tahajudnya nanti kebablasan.” Betul. Itu
suara isteriku. Tangan-tangan yang menarik-narik kakiku tadi berubah menjadi
tangan yang begitu lembut. Begitu hangat kurasakan.
******
Sebenarnya, kisah cintaku dengan Lezzet—sekarang isteriku—terlalu
menggelikan ketika kuangkat ke dalam sebuah cerita. Lezzet adalah perempuan
ulet, penyabar, hidungnya mancung, alisnya tebal, matanya bulat, lesung pipit,
dan selalu menebarkan senyum manis. Sedangkan aku dalam kondisi 180 derajat terbalik
dari Lezzet. Tapi memang tidak ada yang bisa menentang takdir dan jodoh yang
telah Tuhan tentukan.
Hubunganku dengan Lezzet juga tidak sebagaimana hubungan muda-mudi yang
lain ketika memadu asmara. Hari-hari kita selalu diisi dengan suasa diskusi dan
dialog; tentang politik, soial-budaya, filsafat, dan terlebih lagi soal agama. Kadang-kadang juga kita saling curhat
tentang keluarga di rumah. Tentang ibu yang sering marah, atau tentang sikap
ayah yang sering dingin menanggapi tingkah laku anaknya. Sesekali Lezzet
tersenyum mendengar penuturanku yang jujur itu. Terlebih lagi ketika kukatakan
kesukaan ibuku,”Ibuku paling senang petis. Kalau ibuku lagi marah, aku
menyempatkan diri mampir di toko untuk membelikan dia petis. Pasti rasa
marahnya jadi kendor. Sebentar kemudian sifat keibuan dan rasa kasih sayangnya
kembali akan tercurahkan kepadaku.”
Dua bulan aku memadu asmara dengan Lezzet. Ternyata ibuku mengetahui hal
tersebut. Aku mulai membaca sesuatu yang kurang enak yang terpancar dari raut
muka ibu. Tapi bagaimana lagi. Dua hati yang telah menyatu sangat sulit untuk
dipisah. Bahkan, jauhnya jarak dan luasnya samudera bisa ditempuh atas nama
cinta.
“Hei, anak nggak tahu diuntung! Sudah berani pacaran dengan seorang perempuan.
Dengar, ya! Aku dan bapakmu
dulu nggak kenal yang namanya pacaran. Tapi karena memang ada jodoh, aku dan
bapakmu bisa sampai di pelaminan!”
“Bu, aku nggak pacaran. Aku cuman ketemu Lezzet karena Lezzet butuh
bimbinganku. Benar, Bu! Aku tidak berbuat apa-apa!”
“Butuh bimbingan atau tidak, itu bukan urusanku. Memangnya nggak ada
pembimbing perempuan, hah!”
“Betul, Bu. Aku cuman diskusi dengan dia. Nggak berbuat yang macam-macam,
kok.”
“Eh, kamu tahu nggak. Sudah berapa banyak perempuan hamil di luar nikah.
Pergaulan bebas telah membuat moral anak muda hancur. Aku tidak mau kamu
seperti mereka. Mau ditaruh di mana muka ibu dan bapak, hah!”
Aku hanya terdiam. Aku betul-betul tidak berhasrat melakukan sesuatu yang
melanggar hukum dan agama. Tapi Lezzet telah menjadi bagian dari hidupku di
kolom-kolom diskusi.
Lezzet menangis tersedu ketika mendengar kabar dariku tentang sikap ibu
yang begitu fanatik dan kolot. Lezzet mengusap air matanya dengan kerudung
panjang yang ia pakai. Aku mencintai dan menyayangi ibuku, tapi aku juga tidak
mungkin melupakan Lezzet yang telah melekat dalam setiap garis hari dan bentang
mimpiku.
*******
Walaupun aku akan merasakan sakit yang luar biasa, aku berharap aku tidak
akan bertemu lagi dengan Lezzet. Biarlah Tuhan memelihara kecantikan dan
kegadisannya. Aku teringat pesan Ustadz Fauzan Badri beberapa bulan yang lalu
bahwa kita sering melakukan zina mata, telinga, hidung, mata, dll. Mungkin
akulah termasuk salah satu contohnya ketika aku bertemu dengan Lezzet, walaupun
ada misi dakwah dan menyebarkan ilmu.
Kubuka gorden kamar sambil melihat pepohonan yang indah di kejauhan sana.
Kabut itu masih menyelimuti gunung yang menjulang di depanku. Kulihat ada
seorang perempuan memasuki pekarangan rumahku. Lezzet! Ya, Lezzet masih muncul
lagi di hadapanku. Apakah dia mau membuktikan kegalakan ibuku sehingga begitu
berani datang ke rumahku. Ah, biarlah. Aku tidak akan menemuinya. Biarlah ibuku
yang mengatasi perempuan itu.
“Sudah tiga kali perempuan itu datang kemari,” kata ibu sepulangnya Lezzet.
“Apa, sudah tiga kali? Kenapa ibu nggak ngasih tahu?”
“Hah...?! Apakah kamu masih mau bertemu lagi dengan perempuan itu?”
“Ah, nggak, Bu. Aku hanya bertanya, kenapa ibu nggak ngasih tahu.”
“Dia memang hanya ingin bertemu dengan ibu. Pertama kali datang ke sini dia hanya minta maaf. Kedua kalinya hanya mengantarkan petis.
Begitu juga ketiga kalinya. Katanya, dia begitu mengagumi ibu. Menurutnya, ibu
begitu perhatian terhadap kamu. Padahal, jarang sekali orang tua itu sempat
mengontrol anaknya.”
“Lalu, Bu.”
“Ya, setelah itu langsung pamit pulang.”
Dari raut wajahnya, sangat kelihatan kalau ibu betul-betul tidak menyukai
Lezzet. Tapi anehnya, oleh-oleh petis darinya selalu membuat ibu terlihat
sumringah. Ah, ibu... ibu….! Kisah ini betul-betul menggelikan! Dan ternyata,
rasa geli juga dirasakan Lezzet. Namun, Lezzet masih bersikap secara wajar. Ia
tak menampakkan bahwa ada sesuatu yang ganjil yang terjadi pada diri ibu.
Akhir-akhir ini, hampir setiap minggu Lezzet datang ke rumahku dengan petis kesukaan
ibu. Hingga akhirnya, ibuku takluk dengan jurus maut yang dipakai Lezzet.
********
Dulu, kisah-kisah yang menggelikan antara aku, ibu, dan Lezzet kuanggap
sebagai lelucon penghias kehidupan. Dan tak kusangka bahwa lelucon-lelucon itu
akan menghasilkan sesuatu yang indah di alam nyata. Buktinya, aku dan Lezzet
betul-betul menjadi sepasang suami isteri. Betul juga kata ibuku, takdir dan
jodoh ada di tangan Tuhan.
Malam semakin larut. Sinar rembulan yang menyetubuhi altar kehidupan
membuat terang seiisi hati. Apalagi, bintang gemintang kini bertabur di langit
malam. Tak ada awan yang mengusik indahnya malam. Dan yang membuatku bangga,
malam ini aku tidak perlu mengumpulkan tangga-tangga untuk menyentuh dan
menggendong rembulan. Malam ini aku juga tidak perlu menikmati keindahan alam
dari ketinggian. Aku sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa tanpa harus
melihat danau-danau, selat dan samudera, gunung-gunung, pepohonan, juga
keindahan-keindahan negeri yang membentang luas dihiasi dengan warna indah rembulan.
Kamar yang sempit ini, Tuhan ciptakan sebagai alam yang keindahannya kecipratan
dari syurga. Malam ini aku betul-betul tidak sedang bermimpi, rembulan sedang
berada dalam gendongan.
*Tulisan ini dimuat di Harian Seputar Indonesia,
Minggu, 01 November 2009

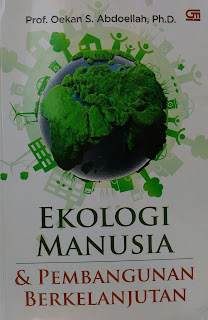

Komentar
Posting Komentar