Aku, Zidah, dan Ira
Sejuknya suasana Fakultas Sastra Universitas Jember membuat aku betah
menjalani kehidupanku sehari-hari. Aku bisa berkenalan dengan mahasiswa dari berbagai daerah; Madura,
Sumatera, Banyuwangi, dll. Aku juga bisa berkenalan dengan para dosen dan
bercerita banyak tentang budaya asli daerahku; Yogyakarta. Aku sedikit ciut
ketika aku tahu bahwa rata-rata dosenku pernah kuliah di Universitas Gadjah
Mada dan mengenal banyak tentang budaya Yogya.
Setahun kemudian aku berkenalan dengan seorang mahasiswi MIPA jurusan
biologi. Aku tertarik dia karena dia suka bercerita sebagaimana aku suka
menulis cerpen. Namanya Zidah. Dia berasal dari Lamongan dan pernah nyantri di
Gresik selama enam tahun.
Pada awal tahun baru, aku sengaja mengajaknya makan di sebuah restoran dekat Matahari Dept. Store.
Kebetulan kami suka menu makanan yang sama walaupun minumnya berbeda. Dia suka
es jeruk sedangkan aku lebih suka minum kopi susu.
Minggu pagi selepas mengitari alu-alun aku mengatakan bahwa minggu ini aku
ada acara penelitian di Banyuwangi.
“Tantang Mantra Jaran Goyang,” kataku.
“Wah, hebat Sampeyan. Nanti bisa melet cewek yang ayu-ayu di Fakultas
Sastra. Iya, kan?”
“Iya. Tapi bukan mahasiswi Fakultas Sastra. Aku nggak senang menjalin
asmara dengan teman sekampus.”
“Kenapa, Mas.”
“Frekwensi pertemuan itu sangat menentukan kadar rindu dan cinta bagi
diriku. Semakin sering aku bertemu, statistik rindu dan cintaku semakin rendah.
Dan semakin jarang aku bertemu, luapan emosi untuk memiliki semakin tak
terbendung.”
“Alaahh…anak sastra ya ngono. Pandai bermain dengan kata-kata
dan merayu.”
Sebenarnya aku tidak bermaksud merayu. Aku juga tidak sekedar bermain
dengan kata-kata agar aku dapat dipercaya. Aku lebih suka mengungkapkan isi
nurani. Aku lebih menghormati kejujuran walaupun sering berkhir dengan
penderitaan dan luka. Aku juga tidak suka menyakiti hati seorang perempuan,
apalagi perempuan se ayu Zidah. Keputusanku untuk memilikinya bukan
sekedar asal-asalan dan tanpa pertimbangan. Tapi hal itu melalui proses panjang
dan penuh pemikiran.
Sehari menjelang keberangkatanku ke Banyuwangi, seakan ada tangan raksasa
yang menahan langkah kakiku agar aku tidak pergi. Aku berat berpisah dengan
Zidah walaupun perpisahan itu hanya satu minggu. Apalagi ketika Zidah tahu
bahwa aku berangkat tidak sendiri, melainkan dengan Ira, teman seangkatan asli
Banyuwangi.
“Ira pasti lebih ayu,” katanya dengan pandangan jauh ke depan.
“Ira asli Banyuwangi. Aku yakin dia nanti banyak membantuku dalam
penilitian. Apalagi dia banyak tahu tentang seluk-beluk Banyuwangi dan orang
yang memiliki Mantra Jaran Goyang.”
Senin pagi, Zidah mengantar kepergianku. Mukanya sangat layu, selayu kembang
yang akarnya tak menghirup air selama seminggu. Apalagi ketika dia menatap
wajah Ira. Ada nada cemburu yang terselip di hatinya. Seakan dia mengantarkan
kepergianku yang tiada akan pernah kembali. Percayalah, sayang. Aku akan
kembali.
*****
Seusai menyusun laporan penelitian, aku dan Ira langsung menghadap Pak Ayu
Sutarto untuk mendiskusikannya. Ia seorang budayawan alumnus Universita Gadjah
Mada Yogya. Pengalamannya di bidang penelitian tidak dapat disangsikan lagi. Ia
pernah mengadakan penelitian di Leiden, Belanda selama dua tahun. Aku senang
Pak Ayu. Orangnya santai. Sesekali ia menyampakan anekdot-anekdot yang membuat fresh
jalan pikiranku. Ia juga senang mengkritik setiap tulisan kami yang menyimpang
dari aturan. Walaupun masih banyak revisi, kami senang dan bangga atas cara
kerja dan karya kami. Terasa tak ada beban dalam rongga dada dan hatiku. Tapi
bagaimana dengan Zidah?
Setelah mendiskusikan hasil penelitian tersebut, siang itu aku langsung
menemui Zidah. Aku mengajaknya makan di restoran langganan kami. Restoran murah
dekat Matahari Dept. Store. Aku bercerita banyak tentang Banyuwangi,
Mantra Jaran Goyang, dan pengaruhnya. Tapi Zidah menanggapi dengan sikap
dingin. Sedingin es yang belum tersentuh di depannya.
“Mas nggak mau bercerita tentang Ira?”
Aku hanya tersenyum kecil. Aku faham betul tipe perempuan seperti Zidah.
Satu hal yang paling kusukai darinya: dia pencemburu. Rasa cemburu tidak akan
timbul tanpa adanya tekanan cinta di dalam hati. Semakin tinggi volume cemburu
seseorang, semakin tinggi pula rasa cinta yang ia miliki. Tapi ingat, rasa
cemburu sering menimbulkan konflik dan perpisahan.
Sebulan kemudian aku didaftarkan
fakultas untuk mengikuti Diklat Cipta Karya Sastra di Universitas Islam
Indonesia-Sudan, Malang. Aku bangga bisa jadi duta fakultas walaupun hanya
sebatas mengikuti pendidikan dan pelatihan.
“Bisa membawa teman, Bu?” tanyaku pada ketua jurusan.
“Kamu nanti bersama Ira.”
“Maksud saya, saya mau bersama teman saya dari MIPA,” jelasku.
Bu Asrumi hanya tersenyum. Sebuah senyum yang merupakan jawaban paling
jujur,’tidak boleh!’
Aku hanya menghela nafas panjang seraya memikirkan bagaimana cara
menghadapi Zidah dan mengatasi rasa cemburunya. Pasti dia bilang,”Lagi-lagi
dengan Ira!”
Perpisahanku dengan Zidah terasa lebih berat daripada perpisahan ketika aku
melakukan penelitian di Banyuwangi. Beban yang menggumpal di benakku tak mampu
kusingkirkan hingga aku menginjakkan kaki di Kota Dingin, Malang. Ira jadi serba salah. Mungkin ia merasa
risih dan merasa tidak enak. Tapi sudah kujelaskan tentang Zidah yang sering
cemburu dan aku sangat menyukai perempuan seperti itu.
Hotel Wisma Bhayangkara pagi itu terasa sangat sejuk. Tapi rasa sejuk itu
tak mampu menembus dinding hatiku yang galau. Kuambil segelas kopi yang
tersedia di atas meja. Kusulut sebatang rokok sisa di perjalanan kemarin.
“Hai, bagaimana istirahatnya semalam?” tanya Ira seraya menuju ke arahku.
“Sangat nyenyak. Semua rasa capek hilang. Aku menemukan semangat
baru,”jawabku, pura-pura. Aku menyesal. Nuraniku seakan berontak. Mengapa aku
harus berbohong. Bukankah aku lebih menghormati sebuah kejujuran walaupun
sering berhadapan dengan luka dan derita.
Aku kagum Ira. Sejak dulu. Ia adalah seorang perempuan yang punya etos
kerja tinggi. Setengan bulan yang lalu
ia ikut kemah besar kepramukaan di Banyuwangi. Setelah itu ia harus ke Jakarta
sebab kakak kandungnya sakit parah. Tapi tak terlihat letih dan capek di
wajahnya. Yang ada hanya semangat. Dan rasa semangat itu seakan mengalir ke
dalam jiwaku. Aku tidak tahu, mengapa.
Hari ke dua di Malang, aku sedikit
bisa melupakan konflik diri dengan Zidah. Diklat seharian penuh membuatku
semakin mencintai sastra. Terlebih lagi
nara sumbernya sangat lincah dan lihai
menyampaikan materi. Aku juga banyak berkenalan dengan beberapa mahasiswa dari
berbagai perguruan tinggi; STSI Bali, Unijoyo Madura, dan UM serta Unibraw
Malang.
Pagi ini suasana Fakultas Sastra Universitas Jember terasa lain dari
hari-hari yang lalu. Jam sembilan nanti aku dan Ira harus melaporkan segala
kegiatanku ke ketua jurusan selama di
Malang. Tapi entah kenapa, aku betul-betul mengagumi Ira. Ira adalah sosok
perempuan yang punya semangat tinggi. Ia lincah di berbagai forum dialog dan
diskusi. Ia juga sangat sederhana dan mau menghargai teman. Ia juga terpilih
jadi mahasiswi berprestasi tahun akademik 2003-2004. Walaupun sosok Ira
bukanlah sosok perempuan yang sempurna, tapi nyaris. Aku bukan hanya kagum,
tapi ada rasa lain yang aku sendiri hampir tidak mempercayai.
‘Mas tidak mau bercerita tentang Ira?’ kata-kata itu terngiang lagi di
telingaku. Kata-kata yang dulu diungkapkan Zidah sesudah aku mengadakan
penelitian di Banyuwangi bersama Ira. Kata-kata itu kuanggap sebagai sesuatu
yang lucu dan tidak akan berdampak apa-apa. Tapi mengapa, tiba-tiba aku menyetujui
rasa cemburu yang ada di benak Zidah selama ini. Mungkinkah Mantra Jaran Goyang
telah merasuk ke dalam jiwaku? Ira, betulkah hal itu terjadi? Aku serba salah
dan serba tidak tahu mengambil langkah yang paling bijak. Ira, Zidah, maukah
kalian kujadikan…? Jember, 14
Maret 2004
*Tulisan ini dimuat di Majalah TERAPI 2004

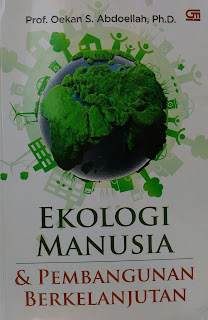

Komentar
Posting Komentar